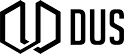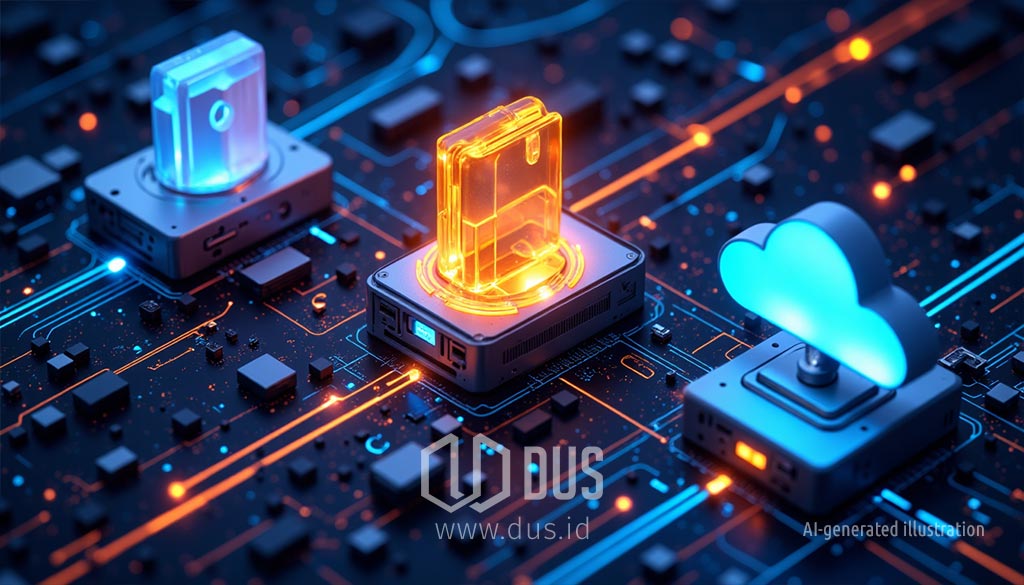Now Reading: Serial Menunda Dewasa 4: Adultolescence – Hidup di Antara Remaja dan Dewasa
-
01
Serial Menunda Dewasa 4: Adultolescence – Hidup di Antara Remaja dan Dewasa

Serial Menunda Dewasa 4: Adultolescence – Hidup di Antara Remaja dan Dewasa
Peter Pan Syndrome menggambarkan penolakan aktif terhadap kedewasaan, terutama pada dewasa muda. Tapi ada fenomena lain yang lebih luas dan lebih diam-diam: adultolescence. Ia bisa dialami oleh siapa saja, bahkan mereka yang sudah berusia 30, 40, atau 50 tahun — orang-orang yang tidak menolak dewasa, tapi belum benar-benar sampai ke sana.
Adultolescence adalah transisi yang tertunda. Bukan karena malas, bukan karena tidak tahu arah, melainkan karena dunia modern menghadirkan tantangan yang membuat kedewasaan tak lagi linear. Banyak orang dewasa secara biologis masih hidup dengan pola remaja: bergantung secara finansial atau emosional, menghindari komitmen jangka panjang, dan belum membangun struktur hidup yang stabil.
Artikel ini mengajak kita menyelami fenomena adultolescence secara sosial, psikologis, dan budaya. Kita akan menggali akar, gejala, dan dampaknya, serta membuka ruang refleksi: bagaimana membangun kedewasaan yang relevan di dunia yang terus berubah — tanpa harus memaksakan versi kedewasaan yang usang.
Bagian 1: Dewasa Secara Usia, Remaja Secara Gaya Hidup

Bayangkan seorang perempuan berusia 42 tahun. Ia bekerja sebagai konsultan lepas, punya penghasilan yang cukup, dan aktif di media sosial. Namun ia masih tinggal bersama orang tuanya, menghindari relasi yang berkomitmen, dan menghabiskan akhir pekan dengan belanja impulsif dan binge-watching. Ia bukan anak-anak. Tapi ia belum sepenuhnya dewasa.
Fenomena ini bukan kasus tunggal. Banyak orang dewasa — bukan hanya dewasa muda — hidup dalam pola serupa. Mereka memiliki tanggung jawab parsial, namun belum membangun struktur hidup yang berkelanjutan. Ada perasaan stagnan, kebingungan arah, dan ketergantungan yang tidak terlihat dari luar.
Pertanyaannya: Apakah kedewasaan selalu datang bersama usia? Atau justru, kedewasaan kini menjadi proses yang lebih kompleks, personal, dan penuh tantangan baru?
Bagian 2: Definisi Adultolescence — Kedewasaan yang Tak Lagi Linear

Jika Peter Pan Syndrome adalah penolakan aktif terhadap kedewasaan, maka adultolescence adalah penundaan yang pasif namun berlarut. Ia bukan bentuk pembangkangan, melainkan cerminan dari dunia yang membuat kedewasaan menjadi proses yang tak lagi jelas ujungnya. Banyak orang dewasa — bahkan yang sudah berusia matang — menemukan diri mereka masih hidup dalam pola remaja: bergantung secara finansial, menghindari komitmen, dan belum membangun struktur hidup yang berkelanjutan.
Istilah adultolescence pertama kali muncul dalam kajian sosiologi dan psikologi perkembangan untuk menggambarkan fase dewasa yang belum sepenuhnya menjalani peran dewasa. Ini bukan gangguan mental, melainkan fenomena sosial yang makin umum, terutama di masyarakat urban dan digital. Ia mencerminkan perubahan struktur ekonomi, budaya, dan psikologi yang memengaruhi cara kita tumbuh dan membentuk identitas.
Berbeda dari Peter Pan Syndrome yang sering muncul pada dewasa muda dan bersifat defensif, adultolescence bisa dialami oleh siapa saja yang merasa “terjebak” di antara dua dunia. Seseorang bisa sadar bahwa ia belum sepenuhnya dewasa, bahkan merasa frustrasi, tapi tetap tertahan karena tekanan eksternal atau kebingungan internal. Kedewasaan, dalam konteks ini, bukan sesuatu yang ditolak — melainkan sesuatu yang belum berhasil diraih.
Bagian 3: Gejala dan Manifestasi dalam Kehidupan Sehari-hari

Fenomena adultolescence bukan sekadar gaya hidup yang terlihat muda, melainkan pola eksistensial yang menyentuh cara berpikir, merespons tanggung jawab, dan membentuk arah hidup. Gejalanya bisa muncul dalam berbagai bentuk, baik yang kasat mata maupun yang subtil secara psikologis:
- Ketergantungan Finansial dan Emosional Meski Sudah Dewasa. Banyak individu yang secara usia sudah dewasa masih bergantung pada orang tua atau pasangan untuk kebutuhan dasar—mulai dari tempat tinggal, pengambilan keputusan, hingga dukungan emosional. Ketergantungan ini bukan karena tidak mampu, melainkan karena belum terbentuknya rasa otonomi dan kepercayaan diri untuk berdiri sendiri. Dalam banyak kasus, ada rasa nyaman yang bersembunyi di balik ketakutan akan kegagalan atau penolakan sosial. Ini bukan soal tidak punya uang, tapi belum punya struktur hidup yang mandiri.
- Gaya Hidup Impulsif, Konsumtif, dan Minim Perencanaan Jangka Panjang. Pola hidup yang didorong oleh dorongan sesaat — belanja impulsif, binge-watching, scroll media sosial tanpa henti — menjadi pelarian dari tekanan hidup dewasa. Perencanaan jangka panjang terasa membosankan atau menakutkan. Akibatnya, keputusan besar seperti menabung, investasi, atau membangun karier sering ditunda karena tidak memberikan kepuasan instan. Di balik impulsivitas, ada pola pikir kekanakkanakan yang belum terbiasa menunda gratifikasi demi tujuan jangka panjang.
- Penundaan Milestone Dewasa: Menikah, Punya Anak, Karier Tetap. Bukan semua orang harus menikah atau punya anak, tentu. Tapi dalam konteks adultolescence, penundaan ini sering bukan karena pilihan sadar, melainkan karena ketakutan akan komitmen, ketidakpastian arah hidup, atau perasaan belum “siap” yang terus berulang. Karier pun sering kali berpindah-pindah tanpa fondasi yang jelas, karena struktur kerja tetap terasa mengekang atau menakutkan. Milestone dewasa bukan sekadar pencapaian sosial, tapi cerminan kemampuan membangun struktur hidup yang berkelanjutan.
- Kesulitan Membentuk Rutinitas dan Struktur Hidup yang Berkelanjutan. Banyak orang dalam fase adultolescence hidup dari satu hari ke hari berikutnya tanpa ritme yang stabil. Bangun siang, kerja acak, tidur larut, dan pola makan tidak teratur menjadi bagian dari gaya hidup yang tidak terstruktur. Ini bukan hanya soal disiplin, tapi soal belum terbentuknya fondasi psikologis untuk mengatur diri dan menetapkan prioritas. Struktur hidup bukan penjara, tapi wadah untuk tumbuh. Tanpa struktur, arah hidup mudah kabur.
- Perasaan Stagnan, Krisis Identitas, dan Kebingungan Arah Hidup. Mereka yang mengalami adultolescence sering merasa “terjebak” — tidak lagi cocok dengan dunia remaja, tapi belum menemukan tempat di dunia dewasa. Ada kebingungan identitas, rasa tidak cukup, dan pertanyaan eksistensial yang terus berputar: Siapa saya sebenarnya? Mau ke mana hidup saya? Ini bisa memicu kecemasan, rasa rendah diri, bahkan depresi ringan yang tidak disadari. Stagnasi bukan karena tidak bergerak, tapi karena tidak tahu ke mana harus melangkah.
Pola Pikir Kekanakkanakan: Akar yang Menyuburkan Gejala Lain
Di balik semua gejala di atas, ada satu akar yang sering luput: pola pikir yang belum matang secara emosional dan kognitif. Ini bukan soal bersikap ceria, santai, atau playful — karakteristik yang justru bisa menjadi bagian sehat dari kepribadian dewasa. Yang dimaksud di sini adalah cara berpikir yang belum siap menghadapi kompleksitas hidup dewasa: ketidakpastian, tanggung jawab jangka panjang, dan dilema moral yang tidak selalu punya jawaban hitam-putih.
Pola pikir kekanakkanakan ini sering kali ditandai oleh:
- Pemrosesan emosi yang reaktif dan tidak stabil.
- Kebutuhan validasi eksternal yang tinggi.
- Ketidakmampuan menunda gratifikasi.
- Pola pikir biner dan simplistik.
- Penghindaran terhadap tanggung jawab eksistensial.
Pola pikir ini bukan sesuatu yang harus disalahkan, tapi perlu disadari. Ia bisa terbentuk karena pengalaman masa kecil, tekanan sosial, atau bahkan karena dunia modern yang terus mendorong kita untuk tetap muda, bebas, dan tidak terikat. Tapi jika dibiarkan, ia bisa menjadi akar dari stagnasi yang panjang — di mana usia terus bertambah, tapi arah hidup tetap kabur.
Bagian 4: Faktor Pemicu — Dunia yang Tak Ramah Kedewasaan

Mengapa adultolescence makin umum? Karena dunia modern tidak lagi menyediakan jalur lurus menuju kedewasaan. Beberapa faktor pemicunya antara lain:
- Ekonomi. Biaya hidup yang tinggi, sulitnya akses rumah dan pekerjaan tetap membuat banyak orang muda menunda kemandirian. Bahkan mereka yang sudah berpenghasilan tetap pun sering kali tidak mampu membangun struktur hidup yang stabil karena tekanan finansial yang terus meningkat.
- Budaya Pop. Glorifikasi kebebasan, estetika remaja, dan narasi “forever young” membuat kedewasaan terlihat membosankan atau bahkan menakutkan. Sosok dewasa dalam budaya populer sering digambarkan sebagai kehilangan spontanitas, kreativitas, atau daya tarik.
- Teknologi. Media sosial memperpanjang eksplorasi identitas dan gaya hidup, menciptakan ilusi bahwa semua orang masih “mencari diri”. Platform digital mendorong performativitas dan pembandingan konstan, yang membuat struktur hidup dewasa terasa kaku dan tidak relevan.
- Pendidikan. Masa studi yang panjang dan transisi kerja yang tidak linear membuat fase dewasa muda jadi lebih lama dan tidak pasti. Banyak lulusan perguruan tinggi yang masih bingung arah, berpindah-pindah bidang, atau kembali ke rumah orang tua karena belum menemukan pijakan.
- Psikologi. Ketakutan akan kegagalan, perfeksionisme, dan tekanan sosial membuat banyak orang menunda keputusan besar dalam hidup. Ada dorongan untuk “menunggu kesiapan”, padahal kesiapan itu sering kali hanya bisa dibentuk lewat keberanian mengambil langkah pertama.
Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan lanskap kehidupan yang tidak ramah bagi struktur dewasa konvensional. Maka, adultolescence bukan hanya fenomena individu, tapi juga cerminan dari sistem sosial yang berubah.
Bagian 5: Dampak Jangka Panjang — Ketika Masa Transisi Menjadi Zona Nyaman

Meski adultolescence bisa menjadi fase eksploratif yang kaya, ia juga menyimpan risiko jika berlangsung terlalu lama:
- Ketidakstabilan emosional dan finansial. Tanpa struktur hidup yang jelas, seseorang bisa terus berada dalam siklus ketidakpastian yang melelahkan secara mental dan material.
- Konflik relasi dan identitas. Ketidaksiapan berkomitmen atau membangun relasi dewasa bisa memicu konflik dengan pasangan, keluarga, atau bahkan diri sendiri. Identitas menjadi cair, tidak punya fondasi, dan mudah terguncang.
- Ketidakmampuan membangun visi hidup jangka panjang. Tanpa arah yang jelas, hidup menjadi serangkaian keputusan jangka pendek yang tidak saling terhubung. Visi hidup menjadi kabur, dan rasa makna pun ikut memudar.
- Perasaan “terjebak” di antara dua dunia. Terlalu tua untuk disebut remaja, tapi belum sepenuhnya diterima sebagai dewasa. Ini bisa memicu rasa malu, isolasi sosial, atau bahkan penolakan terhadap diri sendiri.
Zona nyaman ini bisa menjadi jebakan jika tidak disadari. Kita merasa aman karena tidak harus mengambil keputusan besar, tapi di balik itu, ada stagnasi yang menggerogoti rasa percaya diri dan arah hidup.
Kesimpulan dan Ajakan Reflektif: Membangun Kedewasaan yang Relevan

Adultolescence bukan kegagalan. Ia adalah cerminan dunia yang berubah. Maka, solusi bukan memaksakan kedewasaan versi lama, tapi membangun struktur hidup yang relevan dengan nilai dan konteks pribadi.
Mari bertanya pada diri sendiri:
- Apa arti dewasa bagi saya?
- Apakah saya menunda, atau sedang mencari bentuk kedewasaan yang cocok?
- Apa nilai yang ingin saya pegang saat membangun hidup dewasa?
- Apakah pola pikir saya sudah siap menghadapi kompleksitas hidup, atau masih terjebak dalam reaktivitas dan penghindaran?
Kedewasaan bukan soal usia, tapi soal keberanian membangun hidup yang bermakna dan berkelanjutan. Ia dimulai dari pola pikir yang reflektif, dari struktur hidup yang dipilih dengan sadar, dan dari komitmen untuk tumbuh meski dunia terus berubah.
Di artikel berikutnya, kita akan menyelami bagaimana membangun kedewasaan emosional di era serba instan — sebuah fondasi penting untuk keluar dari zona adultolescence dan membentuk hidup yang lebih utuh.
📖 Baca atau 🎧 Dengarkan Juga:
- 1. Serial Menunda Dewasa 5: Kedewasaan Emosional — Fondasi untuk Melampaui Kidulting, Quarter-Life Crisis, Peter Pan Syndrome, dan Adultolescence.
- 2. Serial Menunda Dewasa 2: Quarter-Life Crisis – Bingung, Mandek, atau Menolak Tumbuh.
- 3. Mengenal Hipotalamus, Pusat Kontrol Otomatis: Menghubungkan Pikiran dan Tubuh untuk Kelangsungan Hidup.
- 4. Terapi Online vs Offline: Mana yang Lebih Efektif untuk Orang Indonesia.
- 5. Persepsi Waktu: Mengapa Waktu Terasa Lebih Cepat Seiring Bertambahnya Usia.
Previous Post
Next Post
-
 01Generasi Multi-Hyphenate: Menavigasi Era Baru Profesi Ganda
01Generasi Multi-Hyphenate: Menavigasi Era Baru Profesi Ganda -
 02Terobosan Medis: Cahaya Harapan di Tengah Penyakit Kronis
02Terobosan Medis: Cahaya Harapan di Tengah Penyakit Kronis -
 03Menguasai Seni Mengepak: Panduan Efisien untuk Liburan Panjang
03Menguasai Seni Mengepak: Panduan Efisien untuk Liburan Panjang -
 04Menjelajahi Ruang Batin: Seni Produktif dalam Kesendirian
04Menjelajahi Ruang Batin: Seni Produktif dalam Kesendirian -
 05Harmoni dalam Tubuh: Bagaimana Organ Kita Bekerja Sama
05Harmoni dalam Tubuh: Bagaimana Organ Kita Bekerja Sama -
 06Dark Sky Tourism: Berburu Langit Paling Gelap untuk Menikmati Bintang yang Tak Terbatas
06Dark Sky Tourism: Berburu Langit Paling Gelap untuk Menikmati Bintang yang Tak Terbatas -
 07Kopi Specialty: Rahasia di Balik Rasa Unik Kopi dari Berbagai Daerah dan Manfaat Holistiknya untuk Kesehatan
07Kopi Specialty: Rahasia di Balik Rasa Unik Kopi dari Berbagai Daerah dan Manfaat Holistiknya untuk Kesehatan